Tulisan ini menyajikan perbandingan fundamental antara struktur sosial feodalisme yang kaku dengan dinamika sosial dalam tradisi pesantren di Indonesia. Perbandingan ini didasarkan pada pandangan Prof. Dr. KH. Abd A’la Basyir, Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022–2027, yang menempatkan pesantren sebagai ruang mobilitas sosial berbasis meritokrasi sebuah sistem yang sangat kontras dengan sifat statis dan tertutup dari struktur sosial feodal.
Karakteristik Sistem Feodalisme: Status Sosial yang Statis
Sistem feodalisme dicirikan oleh tatanan sosial yang dibangun di atas hierarki yang kaku dan bersifat turun-temurun. Dalam sistem ini, status sosial seseorang ditentukan oleh kelahiran (askriptif), kepemilikan tanah, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Penentu Status dan Mobilitas
Penentu Status: Kelahiran, hak waris, dan kepemilikan tanah.
Sifat Mobilitas Sosial: Statis dan tertutup. Batas antar kelas sosial seperti bangsawan, rohaniawan (klerus), dan petanihampir tidak dapat ditembus.
Sebagaimana ditekankan oleh Prof. Basyir, “Status sosial dalam sistem feodalisme bersifat statis; kelas hamba tani tidak akan pernah berevolusi menjadi bangsawan, apalagi raja.” Pernyataan ini menegaskan bahwa mobilitas vertikal sosial dalam struktur feodal hampir mustahil terjadi. Status individu merupakan warisan yang melekat (ascriptive status), bukan hasil dari usaha atau prestasi pribadi. Akibatnya, sistem ini memperkuat ketimpangan sosial dan mempertahankan dominasi kelas tertentu dari generasi ke generasi.
Karakteristik Tradisi Pesantren: Dinamika dan Mobilitas Sosial
Berbeda secara mendasar, tradisi pesantren, khususnya di Indonesia, menampilkan struktur sosial yang jauh lebih terbuka, egaliter, dan berbasis prestasi (meritokratis). Di lingkungan pesantren, status sosial individu tidak ditentukan oleh keturunan atau garis darah.
Mekanisme Mobilitas Meritokratis
Status sosial dalam pesantren ditentukan oleh prestasi dan kontribusi yang nyata, menciptakan ruang bagi mobilitas sosial vertikal yang terbuka. Prof. Basyir menyatakan, “Sementara kelas sosial di dunia pesantren bersifat dinamis; status sosial santri bisa saja berevolusi menjadi ustaz, dari status ustaz sangat mungkin berevolusi menjadi kiai.”
Kenaikan status dari santri (murid) menjadi ustaz (guru/pengajar) hingga kiai (pemimpin keagamaan tertinggi) dicapai melalui:
Penguasaan Ilmu: Kedalaman dan keluasan pengetahuan agama Islam (keilmuan).
Pengabdian (Khidmah): Loyalitas, dedikasi, dan kontribusi terhadap pengembangan pesantren dan masyarakat.
Pendidikan dan Transmisi Ilmu: Keterlibatan aktif dalam proses mengajar dan membimbing generasi berikutnya.
Dengan demikian, struktur sosial pesantren berfungsi sebagai wadah pembentukan elite keagamaan melalui mekanisme yang bersifat inklusif dan berbasis prestasi (meritocratic status), di mana kerja keras dan keilmuan adalah penentu utama.
Perbandingan dan Implikasi Sosial
Perbandingan yang diajukan oleh Prof. Basyir secara eksplisit menegaskan bahwa feodalisme dan tradisi pesantren adalah dua sistem sosial yang berlawanan secara fundamental. Perbedaan pokok terletak pada mekanisme penentuan status sosial dan sifat mobilitasnya.
Ringkasan Perbedaan Sistem Sosial
| Sistem | Penentu Status Sosial | Sifat Mobilitas Sosial |
| Feodalisme | Kelahiran, hak waris, kepemilikan tanah | Statis, tertutup (Ascriptive) |
| Pesantren | Pendidikan, ilmu, pengabdian, reputasi | Dinamis, terbuka (Meritocratic) |
Implikasi Sosial dan Pendidikan
Perbedaan struktural ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap transformasi sosial dan pembangunan sumber daya manusia:
Agen Transformasi Sosial: Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan juga agen perubahan sosial yang vital. Ia menyediakan jalur bagi individu dari latar belakang ekonomi dan sosial sederhana untuk naik ke posisi kepemimpinan melalui pendidikan dan pengabdian.
Penegakan Meritokrasi: Tradisi pesantren menegakkan etos meritokratis, di mana kedudukan sosial didasarkan pada kapasitas intelektual dan moral, bukan pada asal-usul keluarga. Ini menciptakan budaya yang mendorong kompetisi sehat dan kemajuan sosial berbasis prestasi.
Jalur Sosial Alternatif: Secara implisit, perbandingan ini adalah kritik terhadap sistem sosial yang tidak adil dan eksklusif. Pesantren tampil sebagai “jalur sosial alternatif” yang inklusif di tengah masyarakat tradisional Muslim Indonesia, memperkuat perannya dalam pembangunan sosial-keagamaan yang berkeadilan.
Oleh karena itu, pesantren memainkan peran strategis dalam memperkuat mobilitas sosial vertikal dan membangun masyarakat yang lebih egaliter. Lembaga ini tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga mengembangkan modal manusia (human capital) yang berperan penting dalam kemajuan bangsa.
Referensi
Kutipan Utama (Substansi Pernyataan): Prof. Dr. KH. Abd A’la Basyir, Rais PBNU (2022–2027). Disampaikan dalam acara Silaturahim Nasional (Silatnas) PP Annuqayah Latee, Sumenep, Madura.
Catatan: Substansi pernyataan merujuk pada laporan kegiatan dan konteks penyampaian beliau, mengingat transkrip lengkap pidato tidak tersedia secara publik.
Profil Tokoh: NU Online Jawa Timur. “Profil KH Abd A’la Basyir.” Diakses melalui laman resmi NU Online Jatim.
Konteks Acara: Liputan Ketik.com mengenai kehadiran KH Abd A’la Basyir pada acara Silatnas PP Annuqayah Latee.




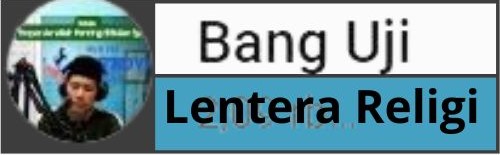
Comment