Hikmah sering diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan kelembutan. Namun, makna hikmah jauh lebih luas dan dalam. Terjemahan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan substansi hikmah itu sendiri.
Para ulama tafsir memberikan berbagai penafsiran terhadap istilah “hikmah”. Thahir Ibn Asyur, misalnya, menyebut hikmah sebagai segala bentuk ucapan atau perbuatan yang bertujuan memperbaiki kondisi dan kepercayaan manusia secara berkelanjutan (Mahulay, 2017). Dalam ilmu ushul fiqh, hikmah dibahas dalam konteks sifat-sifat yang menjadi illat hukum. Sementara dalam tradisi tasawuf, hikmah dipahami sebagai pengetahuan tentang rahasia Tuhan (Hefni, 2003).
Tafsir al-Maraghi mengartikan hikmah sebagai rahasia dan maksud dari hukum serta syariat agama. Ibnu Duraid menyatakan bahwa setiap nasihat yang mengajak kepada kemuliaan atau mencegah dari kejahatan adalah hikmah (Mustafa, 1997). Ibnu Katsir, salah satu mufasir otoritatif, memaknai hikmah sebagai pemahaman terhadap agama. Al-Farabi, filosof Islam, melihat hikmah sebagai pengetahuan tertinggi tentang eksistensi dan kebenaran utama (Bakar, 1997). Sementara itu, Syahrastani, ahli perbandingan mazhab teologi, menyamakan hikmah dengan ilmu filsafat (Syahrastani, 1976).
Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hikmah mencakup pemahaman, ilmu, dan kebenaran dalam Islam. Romly (2009) menyatakan bahwa secara syar’i, hikmah adalah perkataan dan perbuatan yang sahih, mengetahui kebenaran serta mengamalkannya, bersikap wara’ dalam agama, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memberikan jawaban yang tepat serta bijaksana (Dailami, 2019).
Dengan demikian, hikmah harus tercermin dalam ilmu, ucapan, dan sikap hidup Islami yang menjadi landasan dakwah. Beberapa ulama, seperti Mujahid dan Malik, menyebut hikmah sebagai pengetahuan tentang kebenaran. Karena sumber kebenaran adalah al-Qur’an, maka hikmah tidak dapat dicapai tanpa memahami petunjuknya, yang mencakup syariat Islam dan hakikat iman (Suparta, 2013).
Pandangan ini sejalan dengan ungkapan Imam Al-Ghazali bahwa hikmah adalah pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama. Dan ilmu yang paling utama adalah mengenal Allah SWT. Dalam tafsir Kementerian Agama terkait QS An-Nahl:125, hikmah dijelaskan sebagai ucapan yang benar dan tegas yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil.
Hikmah juga harus diimplementasikan dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Seorang da’i dituntut memahami terminologi hikmah secara tepat agar tidak hanya mengikuti opini publik. Pendapat paling representatif menyebut bahwa hikmah adalah petunjuk yang datang dari al-Qur’an dan sunnah, baik berupa perintah, larangan, maupun kabar yang mengandung pelajaran. Oleh karena itu, metode dakwah yang bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah tidak dapat disebut sebagai metode yang hikmah.
Kedalaman makna hikmah menuntut seorang da’i untuk berjuang dalam memahami dan mengimplementasikannya, dimulai dari pembinaan spiritual: ketaatan, kepasrahan, rasa takut kepada Allah, dan sifat wara’ dalam setiap perilakunya. Sikap inilah yang akan menjadikan da’i istiqamah, benar, dan terkendali dalam dakwah, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dengan keteguhan hati.
Hikmah juga berarti kenabian, karena seluruh ilmu dan kebaikan terkandung dalam tugas kenabian, baik dalam ucapan maupun tindakan Nabi. Hikmah ini termaktub dalam sabda-sabda beliau dan harus dipahami oleh umatnya. Imam Jalaluddin as-Suyuthi pun menafsirkan hikmah sebagai ilmu yang bermanfaat dan mendorong manusia untuk berkarya. Maka, orang yang enggan mengembangkan potensinya karena rasa malas dikatakan tidak memiliki hikmah.




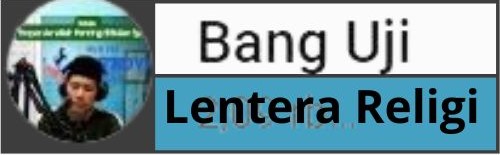
Comment