Interaksi antara Islam dan budaya lokal dalam masyarakat terus menjadi topik kajian yang menarik untuk dikaji. Isu ini telah ada sejak awal pewahyuan Islam di Arab, yang membawa ajaran universal tetapi tetap mengakomodasi konteks sosial dan budaya setempat. Konsep adaptasi ini sangat penting dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, di mana para pendakwah memanfaatkan simbol-simbol yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat.
Strategi Dakwah Wali Songo dan Adaptasi Budaya
Pendekatan adaptif ini terlihat jelas pada metode dakwah Wali Songo, yang merupakan tokoh sentral dalam proses Islamisasi Indonesia. Para wali menerapkan inovasi dakwah yang khas dan berbeda dibandingkan daerah lain. Sunan Ampel dikenal dengan filosofi “moh limo” (meninggalkan lima perkara terlarang), Sunan Kudus memperkenalkan konsep “Gusjigang” (Bagus, ngaji, dan dagang), dan Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan sufistik melalui suluk linglung. Metode ini, yang sering memanfaatkan nuansa filosofis dan sufistik, berhasil menjembatani pemahaman masyarakat Indonesia terhadap ajaran Islam dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami.
Peran Pesantren dan Dinamika Simbol dalam Dakwah
Strategi adaptasi ini kemudian dilanjutkan oleh generasi ulama berikutnya yang berpusat di pesantren. Sebagai institusi pendidikan Islam yang khas, pesantren memainkan peran signifikan dalam mengembangkan simbolisme ajaran Islam yang ramah terhadap budaya lokal. Kiai sebagai motor penggerak pesantren menjadi simbol perjuangan dalam penyebaran Islam. Hubungan interaktif antara kiai dan masyarakat menciptakan dinamika penggunaan simbol dalam dakwah yang menarik perhatian akademisi. Perjuangan pesantren untuk melestarikan simbol-simbol warisan Wali Songo merupakan langkah penting dalam mempertahankan warisan budaya dan agama. Pemaknaan simbol bersifat dinamis dan kontekstual, sesuai dengan konsensus masyarakat pengguna. Seperti yang diungkapkan oleh Clifford Geertz, sistem simbol yang khusus terbentuk dalam komunitas tertentu, mengandung unsur etika dan pandangan dunia mereka. Narasi simbolik ini juga tercermin dalam praktik dakwah tradisional, seperti yang dilakukan oleh Gus Muwafiq Yogyakarta, Gus Bahauddin Nur Salim Sarang dan Kiai Nusantara yang lain.
Inovasi Dakwah di Era Kontemporer
Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, khususnya dengan munculnya generasi milenial, strategi dakwah konvensional seperti ceramah saja mungkin sudah tidak lagi efektif. Diperlukan kreativitas agar pesan Islam dapat disampaikan secara lebih manusiawi dan dialogis. Gus Muwafiq Yogyakarta, Gus Bahauddin Nur Salim Sarang dan Kiai Nusantara yang lain menjadi contoh kiai multidimensional yang berhasil menyesuaikan dakwahnya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Ia dikenal sebagai sosok spiritual, pengusaha, seniman, dan tabib, yang membuat pendekatannya menjadi sangat relevan. Untuk menganalisis strategi dakwah Gus Muwafiq Yogyakarta, Gus Bahauddin Nur Salim Sarang dan Kiai Nusantara yang lain , analisis semiotika ala Roland Barthes digunakan. Pendekatan ini memungkinkan pemaknaan simbol dianalisis secara mendalam melalui dua tahap signifikansi Barthes: denotatif (makna harfiah) dan konotatif (makna budaya yang mencerminkan struktur sosial masyarakat).
Hal ini menegaskan bahwa interaksi antara Islam dan budaya lokal adalah proses yang kaya dan kompleks, menyoroti pentingnya adaptasi agar ajaran Islam tetap relevan dan diterima masyarakat, sembari menjaga nilai-nilai kultural yang telah ada.
Referensi
Geertz, Clifford. The Religion of Java (1960).
Ricklefs, M. C. A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (2008).
Barton, Greg. Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2002) atau artikel-artikelnya mengenai Islam Nusantara.
Barthes, Roland. Mythologies (1957).
Sumber-sumber khusus tentang KH. Abdul Ghofur dan Pesantren Sunan Drajat (artikel jurnal, skripsi, atau buku yang secara spesifik membahas dakwah beliau)




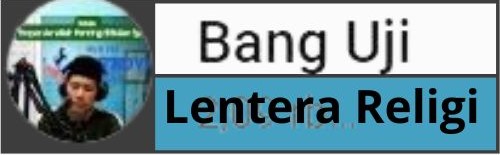
Comment