Istilah “santri” seringkali terlampau rumit untuk didefinisikan. Mungkin, istilah ini sudah begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia sehingga mudah dipahami tanpa perlu penjelasan mendalam. Namun, harus diakui bahwa makna santri telah mengalami pergeseran, bahkan distorsi, membuatnya tercerabut dari wataknya yang asli. Santri tidak lagi menjadi realitas “subkultur” dengan kekhasan dan keunikan budaya yang berbeda dari tradisi umum masyarakat.
Pesantren dipandang sebagai “subkultur”, yang mungkin membingungkan bagi sebagian orang, sama seperti pandangan Geertz pada tahun 50-an yang mengungkapkan bahwa simbol-simbol dalam tradisi Jawa berakar pada Hindu-Buddha, menciptakan subkultur yang terbelah antara santri, priyayi, dan abangan. Para peneliti, termasuk Geertz, sering kali mengabaikan sudut pandang masyarakat yang mengalaminya, hanya mengulangi pendekatan kolonial yang cenderung tidak memperhatikan realitas.
Pada abad ke-19, santri merujuk pada pelajar Islam yang bepergian dan tinggal untuk menuntut ilmu dari seorang kiai. Istilah “kaum putihan” sering digunakan untuk menyebut muslim saleh dalam teks-teks Jawa kuno. Masuknya abad ke-20 membawa pergeseran makna, di mana santri mulai dikenali sebagai individu yang secara ketat mematuhi dasar keyakinan agamanya.
Di abad ke-21, santri lebih sering diasosiasikan dengan politik identitas: berkaitan dengan golongan tertentu yang mungkin memiliki patron sendiri, dan dapat berbeda orientasi satu sama lain. Perubahan sosial berpengaruh pada struktur masyarakat, yang pada gilirannya mengubah pola pikir, orientasi, dan kecenderungan sosio-politik mereka.
Santri masa kini tidak selalu identik dengan figura kesalehan. Cenderung lebih penting bagi mereka tren “identitas politik” dibanding nilai-nilai kesalehan yang mungkin dianggap absurd. Membaca teks-teks Jawa masa lalu memperlihatkan epik para pengelana, di mana pengetahuan simbolik saling terhubung membentuk tradisi “kesantrian” yang kaya dan kokoh dalam budaya Nusantara.
Tokoh-tokoh legendaris santri seperti Aji Saka dan Among Raga lebih mirip dengan pengalaman sufi dalam karya Al-Busyiri, “Kasyful Mahjub”, yang berkelana untuk mencari pengetahuan dan kebijaksanaan, bukan sekadar pertapa yang mengisolasi diri dari keramaian. Pengarang teks-teks Jawa dahulu tidak hanya menciptakan karya klasik, tetapi juga melakukan interteks dengan banyak karya dari daerah lain. Thomas Gibson mengemukakan bahwa karakteristik masyarakat Nusantara dipenuhi nuansa simbolik dalam berbagai bentuk pengetahuan.
Dengan meminjam formulasi Weber tentang “tipe ideal”, Gibson mengaitkan praktik ritual sebagai pengetahuan masyarakat Nusantara dengan otoritas tradisional yang diturunkan dari raja-raja, serta pengetahuan agama Islam yang dipegang oleh para kiai. Semua bentuk pengetahuan simbolik ini dekat dengan apa yang disebut “budaya pesantren”, yang telah mengakar dalam realitas masyarakat Nusantara. Meskipun seorang kiai kharismatik tidaklah “primus inter pares” di antara santri, ikatan simbolik mereka tetap kuat hingga kini.
Namun, budaya santri kini semakin memudar, terutama saat makna santri diseret ke dalam politik identitas, hampir kehilangan sifat tradisionalnya yang menghubungkan kesalehan dengan “kebaratan”; antara “keislaman” dengan “keindonesiaan”. Kini, banyak orang secara tiba-tiba mengklaim diri sebagai santri untuk menegaskan identitas politik mereka, bukan sebagai bagian dari tradisi pengetahuan simbolik yang membangun karakter kesalehan, keislaman, dan keindonesiaan seperti santri kelana di masa lalu.
Ada adagium yang menyatakan, “sekali santri ya santri selamanya,” seolah-olah santri adalah identitas yang melekat dan tak bisa diubah, meski masyarakat terus berubah. Bahkan ada yang mengatakan, “sampai mati ya tetap santri,” yang terdengar sebagai pengakuan berlebihan dan pembenaran diri. Keberadaan “Hari Santri” lebih terlihat sebagai kompromi politik dalam memperluas patronase baru, alih-alih menguatkan budaya pengetahuan atau ritual simbolik yang menghubungkan kesalehan, keislaman, dan keindonesiaan yang humanis dan kosmopolit, bertentangan dengan upaya-upaya tertentu dalam memperkokoh bentuk politik identitas.
Referensi
Gibson, Thomas. (Tahun Terbit). Judul Buku Penerbit.
Geertz, Clifford. (1960). The Religion of Java. University of Chicago Press.
Al-Busyiri. (Tahun Terbit). Kasyful Mahjub




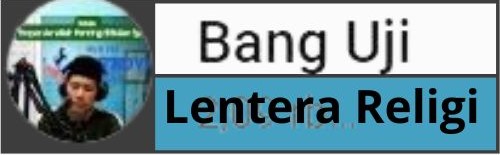
Comment